“Sunguh indah, laut cinta”. Syair ini kucuri untukmu dari BIMBO, merah delima bila dia bertengger di bibir Parlina tetapi ketika kucuri darinya warnanya menjadi jingga retak-retak, melambai bergelombang memporakporandakan langit-langit kelabu.
Hari ini untuk kesekian kalinya engkau merasuki sukmaku. Wajah rembulanmu yang sejuk bagai sejuknya sungai hutan mengalir di mataku. “Kekasih, kemarilah. Tidakkah engkau tahu aku rindu padamu?”
“Sungguh perih, laut cinta”. Sekelabu langit-langit, yang ini kugubah untukmu. Kepada halilintar kupesan: “Bisikkan ini padanya”. Telahkah engkau terima titipan itu? Tahukah engkau bahwa cintaku padamu bagai onak mencabik-cabik dada?
Lamunanku usai sudah tetapi siapa yang berhak mengusaikan cintaku padamu? Malam ini kumohon agar segera aku tertidur, bermimpi tentang dirimu, dan bila itu terjadi, semoga aku tak bangun seabat. Tahukah kau mengapa begitu? Agar seluruh pembuluh darahmu kualiri, kubelai dan kubalut. Ah, aku bermimpi. Untuk keseribu kalinya aku tak dapat menghalau mimpi dari mimpiku. Tentang rinduku padamu akankah hanya mimpi di atas mimpi?
Ingatkah kau kisah ini? Adalah sekuntum bunga bertengger di ujung lungsuran naga itu, tersenyum menggodaku, kupetik dan kusematkan di atas kupingmu. Ada desiran cinta pada setiap kelopaknya dan itu desiran cintaku. Adalah seuntai mawar di sisi tangga rumah kayu tua itu, menunduk malu berbisik di keningku: “Mengapa ada cinta?
Malam membentang menerpa-nerpa cakrawala. Sepi melanda tak kunjung sirna. Subuh menggeliat menapaki buaian bintang. Aku tak juga dapat tidur. Wajahmu melandaku lagi. Malam berlalu mimpipun tiada. Malam yang gelisah tak secuilpun memberiku waktu menari bersamamu, biarlah, apa pedulimu? Pagi ini telah enam kali kusebut namamu dan kali ketujuh aku berteriak memanggilmu. Kau diam. Aku merana lagi. Mimpi lagikah aku? Tidak. Ini lamunan kesengsaraan.
Wahai gunung dan lembah hentikan lamunan ini. Aduh, benciku membuncah-buncah. Tetapi ini hanya sekejap. Wajah, tawa dan senyummu datang lagi, seru, merambati jiwa menggantungku di angkasa rindu.
Seabad kemudian kutemukan kau berselimut akar-akar rumput, tersenyum seperti dulu ketika bola matamu memohonku menyentuh denyut nadimu. Kau berbaring di sampingku. Bersamamu aku hangat dan ini bukan mimpi. Jiwa-jiwa kita membisu. Tak ada lagi bunga, tak lagi mawar bicara, tak ada bintang dan matahari. Yang ada hanya tulang belulang melintang sepi. Kembali kuperdengarkan janjiku: padamu cintaku putih seputih tulang belulangku. Kau terkatup. Kau sepi. Kita bisu tetapi hangat berselimut akar-akar rumput. Yang tersisa: Abadi cinta kita berbaring di atas tulang belulang, rata terkapar. Rata, Tanah!
Hari ini untuk kesekian kalinya engkau merasuki sukmaku. Wajah rembulanmu yang sejuk bagai sejuknya sungai hutan mengalir di mataku. “Kekasih, kemarilah. Tidakkah engkau tahu aku rindu padamu?”
“Sungguh perih, laut cinta”. Sekelabu langit-langit, yang ini kugubah untukmu. Kepada halilintar kupesan: “Bisikkan ini padanya”. Telahkah engkau terima titipan itu? Tahukah engkau bahwa cintaku padamu bagai onak mencabik-cabik dada?
Lamunanku usai sudah tetapi siapa yang berhak mengusaikan cintaku padamu? Malam ini kumohon agar segera aku tertidur, bermimpi tentang dirimu, dan bila itu terjadi, semoga aku tak bangun seabat. Tahukah kau mengapa begitu? Agar seluruh pembuluh darahmu kualiri, kubelai dan kubalut. Ah, aku bermimpi. Untuk keseribu kalinya aku tak dapat menghalau mimpi dari mimpiku. Tentang rinduku padamu akankah hanya mimpi di atas mimpi?
Ingatkah kau kisah ini? Adalah sekuntum bunga bertengger di ujung lungsuran naga itu, tersenyum menggodaku, kupetik dan kusematkan di atas kupingmu. Ada desiran cinta pada setiap kelopaknya dan itu desiran cintaku. Adalah seuntai mawar di sisi tangga rumah kayu tua itu, menunduk malu berbisik di keningku: “Mengapa ada cinta?
Malam membentang menerpa-nerpa cakrawala. Sepi melanda tak kunjung sirna. Subuh menggeliat menapaki buaian bintang. Aku tak juga dapat tidur. Wajahmu melandaku lagi. Malam berlalu mimpipun tiada. Malam yang gelisah tak secuilpun memberiku waktu menari bersamamu, biarlah, apa pedulimu? Pagi ini telah enam kali kusebut namamu dan kali ketujuh aku berteriak memanggilmu. Kau diam. Aku merana lagi. Mimpi lagikah aku? Tidak. Ini lamunan kesengsaraan.
Wahai gunung dan lembah hentikan lamunan ini. Aduh, benciku membuncah-buncah. Tetapi ini hanya sekejap. Wajah, tawa dan senyummu datang lagi, seru, merambati jiwa menggantungku di angkasa rindu.
Seabad kemudian kutemukan kau berselimut akar-akar rumput, tersenyum seperti dulu ketika bola matamu memohonku menyentuh denyut nadimu. Kau berbaring di sampingku. Bersamamu aku hangat dan ini bukan mimpi. Jiwa-jiwa kita membisu. Tak ada lagi bunga, tak lagi mawar bicara, tak ada bintang dan matahari. Yang ada hanya tulang belulang melintang sepi. Kembali kuperdengarkan janjiku: padamu cintaku putih seputih tulang belulangku. Kau terkatup. Kau sepi. Kita bisu tetapi hangat berselimut akar-akar rumput. Yang tersisa: Abadi cinta kita berbaring di atas tulang belulang, rata terkapar. Rata, Tanah!
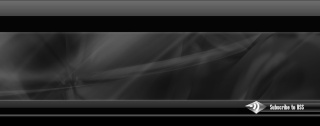

No comments:
Post a Comment