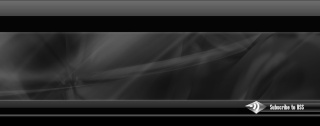“Hidup untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya…”
SEBARIS kalimat di atas keluar dari mulut Pak Harfan (Ikranegara) , seorang kepala sekolah di SD Muhammadiyah, Belitong. Dengan berbekal cita-cita yang tanpa pamrih untuk membagi ilmu kepada anak-anak miskin, mati-matian ia pertahankan sekolah yang sebenarnya sudah layak ditutup itu. Sebuah SD yang pada satu waktu harus menimbang-nimbang antara dilanjutkan atau ditutup berdasarkan jumlah siswa yang mendaftar pada hari pertama di tahun ajaran baru.Pak Harfan tidak sendirian. Ibu Muslimah (Cut Mini), seorang perempuan muda, anak seorang pelopor sekolah Muhammadiyah di Belitong, turut hanyut dalam kegigihan Pak Harfan mencerdaskan anak-anak Belitong yang tidak punya kesempatan masuk sekolah PN Timah yang lebih diperuntukkan bagi mereka yang berduit.Dan, tahun ajaran baru yang bersemangat, mendadak mesti redup dan dihentikan keberlangsungannya karena jumlah siswa yang tidak mencapai sepuluh. Namun niat tersebut menjadi urung setelah seorang anak limabelas tahunan yang memiliki keterbelakangan mental menggenapi angka sepuluh sehingga sekolah bisa tetap berlangsung.
Nama anak itu Harun.Kurang lebih begitulah babak pembuka film Laskar Pelangi garapan Riri Riza yang mengadopsi novel karya Andrea Hirata dengan judul yang sama. Tema mengenai ironi pendidikan, persahabatan, dan semangat hidup, menjadi satu benang merah yang menyulam cerita ini hingga memikat khalayak Indonesia . Kelarisan bukunya yang melebihi angka satu juta kopi, turut menggiring naluri sineas muda seperti Riri Riza untuk mengawetkannya dalam medium yang lebih komunikatif – juga lebih menjual.Film ini berisikan aktor-aktris kawakan seperti Slamet Rahardjo, Lukman Sardi, Ikranegara, Alex Komang, Cut Mini, Mathias Muchus, Tora Sudiro, Robby Tumewu, Rieke Dyah Pitaloka, dan lainnya yang disandingkan dengan duabelas anak-anak asli pulau Belitong.
Cerita dimulai dari alur mundur. Berkisah tentang Ikal dewasa (Lukman Sardi / representatif Andrea Hirata) yang tengah berada di atas bus yang melaju. Lalu menyusul adegan-adegan berikutnya yang menggambarkan masa kanak-kanak Ikal dan kesembilan temannya yang lain: Lintang yang jenius, Mahar sang seniman, Akiong si Tionghoa, Borek alias Samson, Sahara satu-satunya prempuan, Harun yang keterbelakangan mental, Syahdan, Trapani yang rupawan, dan Kucai si kecil yang menjadi ketua kelas. Oleh Ibu Muslimah mereka disebut Laskar Pelangi.Seperti novelnya, hanya beberapa tokoh yang kebagian peran, sedang yang lain figuran sepanjang film. Tentu saja, Ikal dapat porsi paling besar. Karena lewat Ikal-lah penuturan cerita ini bergerak. Lalu berturut-turut disusul porsi bagi Lintang dan Mahar. Akiong, Samson, Kucai, Sahara , dan Harun hanya pelengkap. Bahkan nama Trapani dan Syahdan tidak terdengar sama sekali.
Lewat pembacaan novelnya, alur yang berjalan amat lemah. Begitu datar dan antiklimaks. Hampir tidak ada tujuan ke mana muara cerita in. Hanya sekedar penggambaran keadaan masa kecil Ikal. Fokusnya pun kerap berubah-berubah, tak runut. Padahal, kalau mau mengangkat tema ironi pendidikan, harusnyalah tokoh Lintang disorot dengan lebih intim. Bukan itu saja, setidaknya ada dua data yang keliru dituliskan oleh Andrea, yakni Zubin Mehta yang komposer (padahal seorang konduktor, halaman 128) dan alat musik klarinet yang dikelompokkan dalamjenis brass instrument (padahal woodwind instrument, halaman 234). Sayangnya, kekurangan di novel tidak diantisipasi dengan baik pula di film. Riri Riza masih saja melakukan kesalahan-kesalahan Andrea Hiarata dalam novelnya, walau ada beberapa hal yang berhasil dieksekusi Riri dengan amat baik.
Tertangkap kesan kalau Riri ingin menyederhanakan alur yang dibangun Andrea tapi dalam bobot yang masih ragu-ragu. Keragu-raguan Riri amat terlihat ketika dia berusaha meringkas cerita tapi malah membuat bingung penonton yang tidak membaca novelnya. Misalnya kejadian ketika Flo, tomboy pindahan dari SD PN Timah, hilang di tengah hutan. Sepertinya Riri terkurung dalam perspektif Andrea yang masih hijau dalam meramu cerita. Riri seperti sungkan untuk merekonstruksi cerita bertolak sedikit jauh dari aslinya.Menyaksikan film Laskar Pelangi, penonton serasa menyaksikan penuturan Riri yang ngos-ngosan dalam menerjemahkan sebuah novel. Ngos-ngosan ini terlihat dari usaha Riri yang dengan pasrahmeladeni muatan novelnya yang sebenarnya banyak adegan yang sah bila dihilangkan begitu saja. (walau banyak adegan yang dihilangkan tanpa mengurangi esensi cerita, seperti mengenai ketakutan Ikal menjadi pegawai kantor pos atau mengenai kelompok mistik Societeit de Limpai). Mata dan telinga penonton dipaksa ikut ngos-ngosan pada adegan tidak tercapainya jumlah 10 siswa ketika hari pertama sekolah, pada adegan jatuh cintanya Ikal dengan Aling, serta kepergian Aling ke Jakarta, adegan Samson yang memberitahu Ikal untuk membesarkan badannya dengan bola tenis, atau adegan ketika mereka berkunjung ke Tuk Bayan Tula. Semuanya dipaksakan masuk dalam cerita oleh Riri, tapi seakan-akan dikejar durasi untuk meringkasnya. Jadi terkesan seperti, “Yah…pokoknya ada adegan itu deh”, namun tanpa melayani hasrat intimitas penonton pada tiap detil adegan.
Namun sayangnya, cerita di novel mengenai Aling yang memberikan buku Seandainya Mereka Bisa Bicara kepada Ikal yang dititipkan lewat Akiong, justru dihilangkan. Padahal pada novelnya, juga hubungan dengan seri tetraloginya Laskar Pelangi (buku ketiganya berjudul Edensor), bagian ini amat penting, karena menceritakan sebuah kota bernama Edensor yang menghibur Ikal dengan menggantikan peran Aling.Pemindahan teks ke dalam medium film, yang berhasil dieksekusi Riri misalnya adalah kecerdasannya dalam membeberkan data/fakta dalam novel dalam alur yang tidak runut. Kronologis peristiwa diacak sedemikian rupa, namun tetap menghadirkan data dalam novel. Contohnya adegan ketika Pak Harfan menempelkan poster Rhoma Irama sebagai tambalan dinding sekolah yang jebol, adegan penunjukkan Kucai sebagai ketua kelas, adegan Lintang yang dicegat buaya dan bertemu Bodenga ketika hendak mengikuti lomba cerdas cermat, dan adegan permainan perosotan dengan menggunakan pelepah pisang. Tidak runut, memang. Tapi tetap meramaikan isi cerita.
Hal lain yang perlu dipuji dari film ini adalah ketelitiannya terhadap hal-hal yang detil seperti dialek Melayu, properti yang berdasar pada waktu terjadinya kisah (mobil kuno, sepedamotor kuno, plang di PN Timah yang berejaan lama), kostum, latar, dan pemilihan lokasi syuting. Semuanya persis merepresentasi apa yang ada dalam novel. Dramatisasi yang berlebihan di novel pun diseret paksa oleh Riri menjadi lebih realistis, medekati kewajaran. Misalnya dalam novel dikisahkan dengan amat mengawang-ngawang, tidak realistis, mengenai kejeniusan Lintang. Di novel, pada adegan lomba cerdas cermat, dikisahkan Lintang yang mampu menjawab pertanyaan-pertanya an yang tidak masuk akal untuk anak SD. Sedang di filmnya sangat masuk akal. Misalnya pada adegan ketika jawaban Lintang disalahkan oleh juri. Pada novel, substansi yang didebat adalah soal teori Newton yang ribet. Di film, perdebatan itu hanya menyoal hitungan fisika yang wajar.
Sebaliknya, beberapa bagian malah diberi aksentuasi dramatisasi. Misalnya adegan Ikal yang membeli kapur dan menemukan tangan Aling di balik papan, atau adegan ketika Mahar bernyanyi Melayu dengan diikuti koreografi teman-temannya dengan wajah datar. Namun kedua hal ini justru memberi hiburan tersendiri bagi penonton yang sepanjang film berdurasi 125 menit ini dibuat lelah karena alur cerita yang amat lemah.Buruknya, beberapa bagian tidak tersaji baik: kegigihan Lintang (jauhnya rumah dan perjuangannya tidak terlihat sehebat di novel), kayanya pulau Belitong dan perbadingannya degan kondisi SD Muhammadiyah, adegan ketika pawai karnaval.
Peran dari musik sangat baik. Musiknya tidak terlalu kuat sehingga konsentrasi penonton tidak berpindah kepada musik. Musik benar-benar diposisikan sebagai penguat nuansa. Namun ada potongan musik yang tidak teliti digarap sang penata musik, Aksan dan Titi Sjuman. Kedua drummer suami istri ini terdengar kewalahan mengisi ilustrasi musik pada bagian karnaval. Tampaknya, gerakan tarian pada karnaval sudah melakukan syuting terlebih dahulu dibanding musiknya. Sehingga terlihat usaha musik untuk memberi nuansa lebih kuat tapi seakan berkejaran dengan tempo tarian yang tidak konstan, sehingga menimbulkan pergesaran ritmik antar keduanya yang menyebabkan tidak sinkron.Bagaimana pun, terlepas dari kualitas novel yang biasa saja – hanya beruntung karena mengangkat sebuah tema yang aktual dan seksi – filmnya mampu mengkomunikasikan beberapa hal dengan amat baik. Tema yang diusung dengan dukungan visual dan auditif, mampu memberi efek-efek romantisasi dan melankolik kepada penonton. Laskar Pelangi menjadi sebuah memori yang merekam keprihatinan pendidikan di Indonesia . Sebuah lanskap yang mengguratkan betapa pentingnya bermimpi dengan cinta.